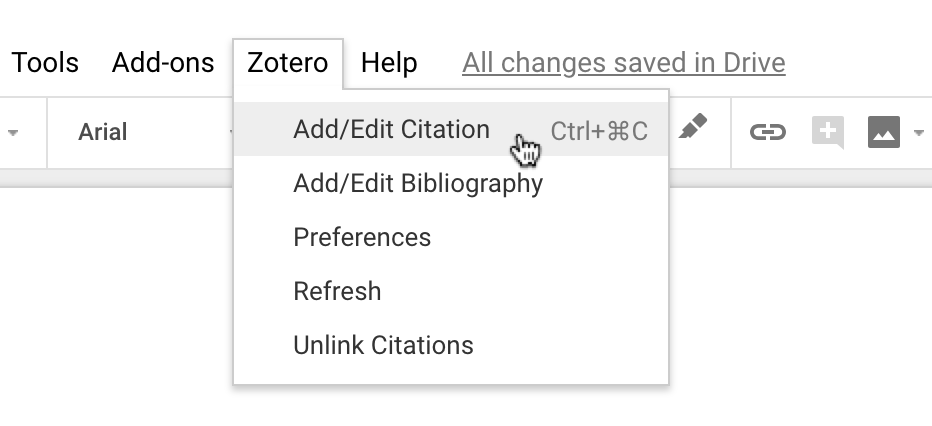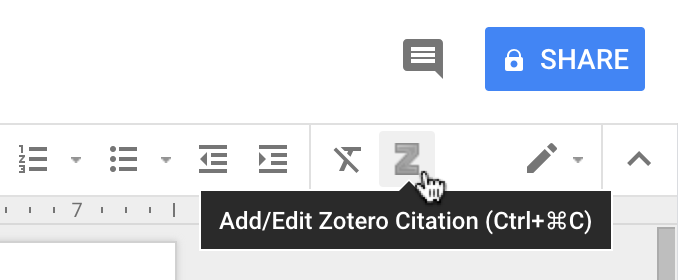Menjadi pustakawan itu berkah. Demikian seharusnya memaknai. Meskipun memang benar, ada yang kemudian berpindah atau keluar dari profesi tersebut. Semua punya sejarah, alasan, dan dasar yang pada dasarnya harus dihormati.
Paijo, pustakawan dari pelosok kampung itu masih mencari pemaknaan dirinya terhadap profesinya. Dia ingin menempatkan pustakawan secara tepat pada dirinya. Penempatan yang pas, ora komplang. Manjing. Tidak menyakralkan, namun juga tidak meremehkan. Pemaknaan ini penting, agar selanjutnya dia bisa merdeka berjalan di jalan yang tepat, dan diyakini. Serta tentunya tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai isu dan dinamika dari luar.
Dia tidak memungkiri, bahwa sesamanya ada yang telah selesai dengan pemaknaan pada profesi ini. Dia anggap begitu beruntungnya mereka. Namun, kadang dia juga berprasangka lain. Mungkin juga mereka tidak begitu memikirkan apa yang sedang difikirkan Paijo. Entahlah.
Paijo yakin bahwa semua pustakawan berhak memaknai perjalanan berpustakawannya. Bahkan pemaknaan itu boleh berbeda dengan orang lainnya. Tidak harus sama. Tidak ada yang mewajibkan harus sama. Tidak ada dosa jika berbeda. Paijo ingat ketika masih sekolah, diskusi bersama teman-temannya tentang tafsir pada ayat suci. Ayat suci yang turun dari Tuhan, ketika sampai pada mufasir akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Jika semua orang yang tidak masuk pada level mufasir ikut menafsirkan, pasti akan lebih beragam. Tafsir pada hal yang sakral pun bisa berbeda, apalagi hanya pada sebuah profesi ciptaan manusia. Demikian yakin Paijo.
Imaji Paijo pun meliar. Ketika di perpustakaan, sambil bekerja, sambil melamun, mencoba menggali makna pekerjaannya. Berharap menemukan titik-titik pemberhentian dan berjumpa dengan makna kepustakawanannya. Untuk mengejar makna ini, buku para begawan juga pernah dibaca, meski tidak semuanya selesai. Apa sebab? Entah. Dia sendiri juga bingung.
###
Paijo melanjutkan perenungan perjalanan kepustakawannya. Kali ini sendirian, tidak ditemani Karyo, yang sedang pergi entah kemana. Juga tanpa sego thiwul kesukaannya. Dia ingin sendiri, kontemplasi. Agar fokus, kontemplasi Paijo dibatasi dahulu sesuai apa yang dia alami: pustakawan formal yang lahir dari pendidikan (ilmu) perpustakaan.
Dalam perjalanan kontemplasi itu, Paijo memilah 3 fase keberpustakawanan yang dia lalui: pre librarian, librarian, dan post librarian. Paijo mencoba menelisik dirinya pada tiga fase ini.
Pre librarian merupakan waktu ketika masih berjuang agar nantinya dapat disebut pustakawan. Berbagai hal dilakukan dalam fase ini. Salah satunya dengan menempuh pendidikan. Pada masa ini idealisme dibangun. Berbagai artikel dan buku dilahap. Berbagai keterampilan diasah. Diskusi didatangi, serta cerdik cendikia didaulat untuk duduk (kadang juga berdiri) berbicara. Tujuannya satu: agar ketika sudah menjadi pustakawan, diperoleh predikat ideal.
Namun, pada masa ini Paijo juga merasa pernah jatuh. Linglung. Dirinya merasa aneh dengan pendidikan perpustakaan yang dia tempuh. ”Iki sekolah opo?”. Kegamangan ini tidak hanya dialami Paijo. Namun juga beberapa temannya. Dibuktikan dengan kenyataan beberapa temannya berguguran, berpindah jurusan sebelum lulus. Bahkan, saat ini pun dia masih menemui mahasiswa yang sekolah perpustakaan merasa gamang. Sialnya, mahasiswa ini pernah bertanya, atau ngudo roso tentang kegamangan ini pada Paijo. Tak banyak yang bisa disampaikan Paijo, “lakukan yang terbaik pada apa yang ada di depanmu saat ini. Kamu boleh tidak suka dengan jurusan yang kamu ambil, tapi jangan remehkan (ilmu) ini”.
Kegamangan itu memang wajar. Seorang yang sudah masuk jurusan favorit macam kedokteran juga bisa gamang. Mungkin ndak sesuai minat, masuk karena ikut-ikutan, disuruh orang lain, atau sebab lainnya. Tapi begitulah, masa pre librarian memang kompleks.
Pada masa ini, Paijo mencoba mengingat, meski ada yang gamang, ada pula yang berfikir idealis penuh percaya diri. Kompilasi bacaan tentang perpustakaan, yang ditulis dari berbagai sumber, mengantarkan mereka untuk presentasi pada pertemuan ilmiah. Atau paling tidak tulisannya menghiasi berbagai media massa. Proses belajarnya harus dibenturkan pada berbagai bentuk pemikiran lainnya. Di pertemuan ilmiah tersebut, pandangan pro kontra akan mematangkan pemikirannya. Pada media massa, orang akan dapat membaca siapa dan bagaimana arah pemikirannya. Ini hal yang positif pada masa pre librarian.
Berikutnya yaitu masa librarian, ketika sudah menjadi pustakawan. Inilah masa seseorang yang sudah menempuh pre librarian, kemudian disebut sebagai pustakawan. Formal. Sesuai undang-undang, atau sesuai ketentuan dan kebutuhan di institusi induknya. Atau mungkin penyebutan itu berasal dari masyarakat sebagai sebuah penghargaan pada peran yang dilakukannya. Pada masa inilah idealisme bertemu dengan realita.
Akan ada kompromi, penyesuaian, pertentangan, dan mungkin penguatan. Kompromi dilakukan ketika menemukan kenyataan yang ternyata tidak serta-merta sesuai dengan jabaran teks yang pernah dibaca sebelumnya, ataupun dengan teks dan interpretasi mutakhir yang juga terus diikuti. Akhirnya ada yang harus ditahan, dikalahkan, diprioritaskan dan lainnya. Hal itu dapat ditelisik dari pilihan bentuk kerja-kerja pustakawan. Inilah masa-masa sulit.
Pada masa ini pustakawan mulai menghadapi konsekuensi yang bukan hanya konsekuensi sebagai pustakawan. Namun juga konsekuensi sebagai manusia. Pustakawan harus mampu membaca dirinya sebagai manusia, bukan sekedar sebagai pustakawan semata. Sebagai pustakawan, diajarkan hal yang ideal: lowongan pustakawan yang menjadi haknya, bisa bekerja, sesuai pendidikan, digaji ideal. Tapi konsekuensi sebagai manusia lebih luas. Manusia itu harus mau diuji, berjalan di jalan yang berliku, penuh perjuangan, dan lainnya. Gajinya sedikit, diberi pekerjaan berlebih, dan lainnya. Ndak enak. Nah, pada masa itulah dia harus memutuskan: lanjut, atau cabut.
Paijo ingat pernah pula dicurhati orang yang ada di level pustakawan. Pelik masalahnya. Bingung pula Paijo dalam menanggapi. Ketika itu, kawan Paijo diminta untuk pindah ke bagian lain. Dia dihadapkan pada pilihan idealisme, atau mengikuti perintah atasan. Paijo memberikan saran yang menurutnya paling barokah: ikuti perintah atasan, selama itu bukan perintah keburukan. Saran ini disampaikan, karena Paijo melihat di unit tersebut kurang orang, dan pada saat yang sama, bagian lain sangat membutuhkan. Kawan tersebutlah satu-satunya pilihan pimpinan. Bagaimana dengan perpustakaan yang ditinggalkan? Dengan pengondisian, dapat berjalan hingga sekarang. Mungkin saran tersebut tidak akan disampaikan, jika ternyata di unit masih ada banyak pilihan orang.
Orang yang (entah) kebetulan atau ditakdirkan jadi pustakawan, harus memandang dirinya sebagai manusia, dan siap dengan segala konsekuensinya sebagai manusia.
Paijo ingat, pada sebuah buku disampaikan bahwa hidup itu ujian, baru kemudian ada pelajaran dari ujian itu. Demikian pula ketika pustakawan masih kuliah, porsi belajarnya baru 20%. Yang 80% main-main. Sementara ketika jadi pustakawan, 100% kesehariannya adalah belajar, praktik, dan ujian. Dia dihadapkan para kenyataan dan ujian. Barulah dari dua hal ini dicari nilai pelajarannya, begitu seterusnya. Itupun jika mampu mencerna ujian yang dihadapi. Jika tidak, maka yang muncul hanya keluhan, umpatan, dan semacamnya.
Sekolah itu pelajaran dulu, baru ujian. Sementara kehidupan alam, ujian dulu baru diberi pelajaran. (sumbernya lupa)
Perjalanan kepustakawanan tidak hanya selesai di sini. Keberpustakawan tidak hanya selesai ketika seseorang menjadi atau mendapat predikat pustakawan dengan berbagai tantangannya. Namun secara substansi, masih bisa naik pada level post-librarian. Beyond librarian.
Post librarian, merupakan masa ketika seorang pustakawan sudah melewati masa “librarian”. Ini posisi terakhir, pungkasan. Pergulatan, kompromi, pertentangan, sudah dilewatinya. Meskipun secara nyata saat itu dia masih menyandang predikat pustakawan, masih melakukan kerja-kerja seorang pustakawan, namun pemaknaannya bisa dinaikkan pada level post-librarian.
Seseorang yang sudah post, berarti sudah selesai dengan berbagai dinamika yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Manjing ajur-ajer. Penempatan arti “pustakawan” pada dirinya sendiri sudah selesai. Konflik, kekecewaan, dan semacamnya yang muncul sewaktu-waktu sudah dapat dia kendalikan di internal dirinya sendiri. Bahkan ketika konflik, kekecewaan, dan semacamnya itu hadir pada ruang dan waktu yang berbeda. Sudah selesai. Dia fokus pada inti profesinya sebagai pustakawan dalam berhubungan dengan orang lain. Inti! bukan atribut.
Menempati posisi post, berarti sudah mapan. Bukan mapan secara finansial, namun mapan secara pemikiran dan pemaknaan. Dia sudah tidak lagi terikat pada dikotomi “saya pustakawan” dan “engkau pemustaka”. Pada taraf inilah, ketentuan pustakawan formal yang terikat undang-undang atau peraturan, sudah tidak berlaku bagi dirinya. Semua manusia itu pustakawan, dan semua manusia sekaligus juga pemustaka.
Inilah masa ketika pustakawan tidak lagi terikat pada batasan: siapa yang berhak menjadi pustakawan, dan siapa itu pemustaka. Baginya, semuanya sudah melebur.
Paijo mengambil nafas panjang. Tatapannya dialihkan ke jalan di depan rumahnya. Jalan yang cukup ramai lalu lalang orang ke tegalan. Kiri kanan jalanan itu tumbuh pohon jati yang rindang. Angin semilir melewati batang pohon, terus dan terus berhembus. Akhirnya sampailah hembusan itu di emperan tempat Paijo duduk. Wajahnya diterpa angin. Wusss. Sejuk. Dia bergumam, “lalu, aku ada pada posisi mana?”. Paijo bertanya pada dirinya sendiri.
Prestasi terbesar pustakawan
Prestasi. Satu kata, namun menjadi tuah sakti untuk banyak orang, berbagai profesi, bahkan berbagai kepentingan. Bermacam kalimat penambah samangat dibuat menggunakan kata “prestasi”: gapailan prestasimu, kejar prestasi, belajar untuk meraih prestasi. Prestasi, secara alami akan dikejar. Bentuknya bisa bermacam, terpaut pada kepentingan si pengejar prestasi itu.
Ada yang menganggap pencapaian pendidikan tertinggi, atau mampu membeli mobil (mewah) sebagai sebuah prestasi. Atau, bagi sebuah partai politik: mempertahankan kekuasaan merupakan prestasi puncak, yang mengikuti prestasi lainnya: merebut kekuasaan.
Demikian pula pustakawan. Ada prestasi yang tertanam pada masing-masing mereka, sebagai angan untuk diwujudkan. Bisa berupa prestasi individu maupun kelompok. Menjadi pustakawan terbaik pada berbagai jenjang, jamak menjadi prestasi yang sering dimunculkan. Baik di level institusi, kabupaten, propinsi, atau nasional. Ya, syukur regional atau internasional. Memperoleh akreditasi ISO, salah satu contoh prestasi institusi yang sungguh merangsang. Menyertainya pula berbagai bentuk prestasi lainnya: mendapat bonus, mendapat beasiswa, presentasi di konferensi, artikel masuk jurnal. Atau mungkin berfoto dengan tokoh penting kepustakawanan idolah dengan berbagai pose aduhai dan gokil, kemudian mengunggahnya ke media sosialnya. Berharap tuah dan berkah melalui tombol like and share. Itu sah dianggap sebuah prestasi yang luar biasa.
Ada juga prestasi harian: mampu menemukan informasi yang dibutuhkan orang lain. Tepat, cepat, dan akurat. Prestasi harian ini mampu meningkatkan hormon kebahagiaan pustakawan di setiap hari. Tentunya prestasi harian ada berbagai macam bentuknya. Semakin sering prestasi ini dicapai, akan berpengaruh pada tingkat kebahagiaan pustakawan. Dia akan merasa dianggap ada dan dibutuhkan. Pihak yang membutuhkan pun merasa terpuaskan.
###
Namun, apa sesungguhnya prestasi terbesar pustakawan?
Sebelum membahas prestasi terbesar pustakawan, ada baiknya kita telaah cara pandang pada profesi pustakawan oleh si pustakawan itu sendiri. Fokus pandangan pustakawan yang mengagungkan pernyataan “pustakawan itu penting”, harus digeser kepada “hal penting apa yang bisa dilakukan pustakawan”. Jika demikian, maka fokus pustakawan akan ada pada perannya, bukan dirinya. Cara pandang ini penting, karena akan mengantarkan pustakawan pada pemaknaan profesi yang luas dan tidak terkungkung pada batasan-batasan tradisional. Meskipun demikian, tetap terkait ruh dasar kepustakawanan.
Prestasi besar pustakawan akan terwujud ketika dikotomi pustakawan-pemustaka sudah tidak ada, sudah hilang. Masa ketika seorang pustakawan akan menganggap orang lain juga merupakan pustakawan. Hal ini bisa dijelaskan dengan filosofi jawa “nguwongke uwong”, menjadi “nguwongke pemustaka”. Pemustaka tidak lagi dianggap sebagai pemustaka saja. Di sisi lain, si pustakawan juga menganggap dirinya sendiri seorang pemustaka, yang memerlukan sebagian kerja kepustakawannya, untuk dirinya sendiri.
Ketika substansi ber-pustakawan telah menempel pada diri setiap pemustaka, maka pada masa inilah, prestasi terbesar seorang pustakawan terwujud. Semua telah pustakawan.
Proses menghilangkan perbedaan pustakawan dan pemustaka ini disebut sebagai proses memustakawankan pemustaka. Hal inilah yang merupakan “hal penting yang bisa dilakukan pustakawan”. Thetek bengek pekerjaan rutin yang selama ini dilakukan pustakawan, merupakan turunan dari hal dasar ini. Proses inilah inti utama kerja pustakawan. Menjadikan pemustaka mampu secara mandiri menemukan informasi yang diperlukan, memfilter kualitasnya, dan menggunakan untuk dirinya sendiri, serta disebarkan kepada orang lain. Atau pemustaka menjadi mampu menemukan komunitasnya sendiri, untuk berkumpul dan bertukar pengetahuan.
Proses di atas, sangat mungkin berakibat pemustaka akan menjadi lebih “pustakawan” daripada si pustakawan. Ini tidak mengapa, justru bernilai positif. Ibarat seorang guru, pustakawan akan merasa bangga jika muridnya telah mampu mengalahkan dirinya. Demikian sabda Begawan Parasurama.
Pada saat inilah, tidak akan ada lagi kekhawatiran hilangnya profesi pustakawan, karena semua orang telah pustakawan. Peran pustakawan menempel pada diri masing-masing manusia (pemustaka), pada semua profesi. Keberpustakawanan merupakan kerja semua orang, bukan monopoli pustakawan formal semata.
Pustakawan hanyalah perantara, lantaran yang hanya opsional agar semua manusia bisa mencapai tingkat berpustakawan untuk dirinya masing-masing.
###
Mendung bergulung tipis. Menurunkan air yang juga tipis-tipis, alias gerimis. Mata Paijo berbinar, senyumnya merekah. Dia merasa memperolah pencerahan. “Kang, ini ada telo godog”, suara lembut istrinya terdengar dari dalam rumah. Keluar sambil nyangking nampan berisi piring berisi ketela mateng yang masih anget, dua cangkir berisi gula batu. Serta teko bercat hijau berisi air teh tubruk, yang tentunya saja masih panas.
Lelaki setengah tua berjalan di bawah gerimis, membawa kail, lewat jalan di depan rumah Paijo. “Mau kemana, Kang?”, sapa Paijo. “Mancing, Kang. Gerimis begini, air agak keruh, ikan mudah untuk dipancing”, jawab Kromo dengan yakin.
Paijo bergumam, "Kang Kromo telah menjadi pustakawan, minimal untuk dirinya sendiri"
 Saya punya kawan. Lulusan sekolah perkebunan, yang dulu belajar tanam-tanaman. Tinggalnya di kawasan, tepat di dekat daerah yang jadi pusat persatean. Tak heran, hobinya pun sesatean. Tidak sembarangan, sate kambing yang dia pesan. Entah berapa porsi sekali pesan. Saya tak tahu, hobi ini murni dari dirinya sendiri, atau pesanan.
Saya punya kawan. Lulusan sekolah perkebunan, yang dulu belajar tanam-tanaman. Tinggalnya di kawasan, tepat di dekat daerah yang jadi pusat persatean. Tak heran, hobinya pun sesatean. Tidak sembarangan, sate kambing yang dia pesan. Entah berapa porsi sekali pesan. Saya tak tahu, hobi ini murni dari dirinya sendiri, atau pesanan.